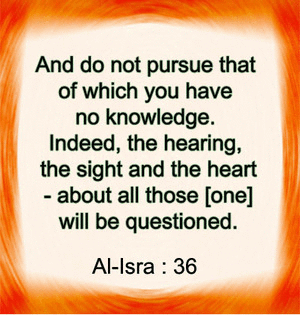Dari lisan suci Sang Nabi, salllahu ‘alayhi wasallam:
“Tidak akan datang kiamat sehingga waktu semakin berdekatan, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejum’at, sejum’at seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam terasa hanya sekejap.”
Dunia palsu, dunia yang dilipat
Jika ada penyair yang mengumandangkan puisi tentang dunia yang penuh kepalsuan, tak pelak lagi, ia pasti sedang membicarakan tentang dunia kita saat ini. Selain membawa berbagai kemajuan, dunia yang telah menjadi global village akibat teknologi transportasi dan komunikasi yang luar biasa, juga membawa kerancuan. Mari bicara tentang sebuah “dunia yang dilipat”. Silahkan bayangkan bahwa dunia ini adalah selembar kertas. Lalu datanglah seorang ahli origami, ia lipat kertas itu menjadi dua, empat, delapan, enam belas, tiga puluh dua, dan selanjutnya. Hingga di satu titik, kertas itu menemui keterbatasan struktur fisiknya. Ia ogah untuk dilipat lagi. Tentu lipatan selanjutnya masih saja bisa dipaksakankan, namun ini adalah lipatan yang menyakitkan. Lipatan yang melampaui batas-batas struktur, karakteristik, dan sifat kertas yang harusnya tidak dilewati. Tindakan memaksa, memadatkan, memampatkan, menekan, dan mengkerdilkan (miniaturisasi) dapat merusak dan mengoyak kertas. Itulah yang terjadi pada dunia kita saat ini; shattered world. Dunia yang terkoyak karena berbagai macam pelipatan dunia yang terlalu dipaksakan.
Bagaimana dunia dilipat? ‘Melipat’ terkait dengan sebuah proses perubahan keadaan (state), khususnya perubahan pada ukuran/luas (teritorial), jarak (ruang-waktu), kecepatan (perseptual), dimensi (bidang-ruang), dan kompleksitas (sosial, budaya). Maka dalam kaitannya, melipat dunia berarti mengandung fenomena pemampatan (ruang-waktu), peringkasan (jarak), pemadatan (kata, bahasa, informasi), reduksionosme (eksistensi) dan pensimulasian (realitas, sosial). Jika melipat selembar kertas berarti mengubah ukurannya menjadi lebih kecil sekaligus menambah ukuran ketebalannya, maka melipat aspek-aspek dunia juga sama;
- ‘Melipat bahasa’ berarti mengurangi jumlah kata sehingga menjadi lebih padat dan ringkas, tetapi sekaligus meningkatkan entropi atau ketidakpastian maknanya. Fenomena ‘bahasa SMS’ adalah sebuah contoh mudah.
- ‘Melipat ruang’ artinya memperpendek waktu yang digunakan untuk menempuh jarak ruang, tapi sekaligus mempersempit ruang relasi fisik dan sosial di dalamnya. Saat ini semua orang bisa berkomunikasi kapan dan di mana saja (real time), namun tidak dengan komunikasi yang leluasa secara fisik dan sosial layaknya tatap muka.
- ‘Melipat waktu’ artinya memampatkan waktu, yakni memperkecil waktu yang diperlukan untuk melakukan pergerakan/perpindahan (movement), namun pada saat yang sama mempersempit waktu refleksi dan perenungan di dalamnya.
- ‘Melipat sosial’ bermakna meredusir sistem, dimensi dan relasi sosial yang kompleks menjadi relasi dengan dimensi yang lebih ringkas (misalnya dimensi citra/imej) namun sekaligus “membunuh” relasi sosial yang nyata. Contoh mudahnya; BBM, facebook & twitter.
- ‘Melipat spiritual’ adalah meredusir dimensi-dimensi spiritual yang kompleks menjadi dimensi tanda dan gaya (sekadar lifestyle), dengan melenyapkan dimensi-dimensi kedalaman dan transedentalnya. Lihatlah fenomena labelisasi ‘spiritual’ atau’Islami’ dan embel-embel keagamaan lainnya pada bermacam konten yang terkadang tidak sejalan –bahkan bertentangan- dengan nilai-nilai keagamaan.
Model Pelipatan Dunia
Ada beberapa model pelipatan dunia. Yasraf Amar Piliang (2004; 50) mengidentifikasi lima model utama, yakni:
- Pelipatan ruang-waktu (time-space compression). Melipat waktu yakni memperpendek jarak waktu (chronos) dengan meningkatkan kecepatan (velocity) atau memperpendek durasi. Sedang melipat ruang artinya memperkecil jarak ruang (spatial) dengan cara memperpendek waktu tempuh dalam ruang itu. Tapi melipat ruang dan melipat waktu adalah dua sisi mata uang, melipat satu berarti yang sekaligus melipat yang lain. Lewat penemuan mutakhir, perkembangan teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah membuat bola dunia menjadi semakin kecil.
- Pemadatan waktu-tindakan (time-action condensation), yakni meringkas sebuah proses dengan melipatgandakan tindakan dalam ruang dan waktu yang sama (multiply of action). Jika dahulu orang melakukan satu hal dalam satu satuan ruang-waktu; memasak, makan, menyetir, dan lainnya, maka kini manusia bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sama; menyetir sambil makan sambil menelepon sambil mendengarkan musik sekaligus berbicara. Terjadilah efisiensi waktu; banyak tindakan berkumpul dalam waktu yang amat sedikit. Zaman ini orang ‘terpaksa’ meminimalkan kualitas tindakan dengan memadatkan waktu tindakan. Efeknya, tindakan dan perbuatan manusia kehilangan maknanya yang mendalam, minim penghayatan dan sublimasi. Orang senantiasa berada dalam kepanikan, ketergesaan dan histeria, seolah-olah selalu diburu waktu (takut kehilangan waktu).
- Miniaturisasi ruang-waktu (time-space miniaturisation). Dalam pengertian ini, ruang dan waktu dikerdilkan, diredusir ke dalam berbagai dimensi, aspek, sifat dan wujud. Adanya ‘malih rupa’ ke berbagai wujud yang lebih ringkas daripada aslinya. Inilah ruang representasi; ruang maya yang memiliki hukum ruang-waktunya sendiri. Maka gambar, fotografi, televisi, film, video dan internet (terutama social-media) telah menjadi dunia sendiri. Dunia simulasi yang terkadang mengambil alih peran dunia nyata. Maka banyak orang mengalami gangguan kehidupan nyata karena ambiguitas kesadarannya yang ter-split antara simulasi dan kenyataan. Lihatlah betapa tidak sehatnya hubungan sosial nyata anak-anak yang menghabiskan sebagian umurnya dalam interaksi simulasi di depan pesawat televisi dan berbagai gadget lainnya.
- Pemadatan ruang-waktu simbolik (symbolic time-space compression). Simbol-simbol dalam interaksi yang sebenarnya merupakan penanda dunia nyata, pun tidak luput dari peringkasan. Ada berbagai mekanisme dalam bahasa, misalnya, untuk menjadikan suatu simbol dapat di-cut dan dikompresi sedemikian rupa, namun pesan dan makna masih bisa sampai. Tapi pada sau titik, pelipatan simbolik ini akan melampaui kemampuan bahasa dalam mengungkapkan makna, sehingga sampai pada suatu titik, di mana pesan dan makna tidak lagi penting. Yang ada hanya permainan kata-kata semata. Lihatlah saat ini betapa banyak orang yang tidak paham akan perkataannya sendiri, berapa banyak pemerkosaan kata-kata dan permainan kalimat (silat-lidah) yang tidak lagi mengandung makna. Akhirnya bahasa mengalami kematian, ia tidak lagi efektif sebagai penyampai pesan.
- Peringkasan ruang-waktu psikis (psychical time-space condensation). Empat model yang telah disebutkan sebelumnya secara langsung ataupun tidak, menimbulkan pengaruh ke dalam ranah psikis. Time-space compression mengubah persepsi tentang jauh dan dekat. Suatu yang jauh dapat terasa amat dekat, sementara sesuatu yang dekat bisa menjadi amat jauh secara psikis. Berapa banyak orang yang punya teman ‘curhat’ yang sangat intim (kendati belum pernah bertemu dan seringkali berinteraksi dengan identitas palsu) di belahan dunia lain lewat internet, sementara ia tidak kenal dengan tetangganya sendiri? Time-space miniaturisation membuat manusia mengalami kerancuan pikir tentang yang nyata dan fantasi, tentang yang asli dan palsu , realitas dan simulasi. kondensasi simbol dan bahasa juga telah merubah persepsi soal makna. kini manusia berbahasa semata-mata untuk pelampiasan hasrat akan perbedaan, bukan lagi sebaga alat penyampai makna. Padahal bahasa adalah tiang utama penyangga budaya. Betapa berangnya saya ketika seorang artis yang minim pengetahuan dan kedalaman makna merancang sebuah kamus bertajuk “kamus gaul” yang memperkosa bahasa sejadi-jadinya, tanpa tanggung jawab apa-apa. Tapi apa boleh buat, ini zaman pop Bung, zaman edan! Begitu pula perkembangan objek-objek (komoditi) sebagai bagian dari dunia simbol (selain bahasa).
Peran objek dalam masyarakat kapitalis dari objek sebagai nilai guna (use value) menjadi nilai tanda (sign value). Baudrillard mengistilahkan zaman ini sebagai zaman kelimpahan. Maka merk dan produk tertentu mengalami estetisasi dan dianggap mewakili etika tertentu. Hal ini yang kemudian melahirkan konsep barang budaya, yang oleh UNESCO diterjemahkan sebagai:
“….barang-barang konsumen yang dapat menyampaikan gagasan, simbol, dan pandangan hidup. Barang ini memberikan informasi atau hiburan, membantu pembentukan identitas kelompok, dan mempengaruhi praktek-praktek budaya. Sebagai hasil daya cipta perorangan atau kelompok –dengan demikian memiliki hak cipta- barang-barang budaya diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya melalui proses industri dan ditribusi global. Buku, majalah, produk multimedia, perangkat lunak, rekaman, film, video, program audiovisual, barang-barang kerajinan dan rancang busana merupakan tawaran-tawaran budaya yang beraneka ragam bagi masyarakat luas.” (Cano, 2005; hal 17-18)
Akhirnya, sistem referensi tradisional telah digantikan oleh sistem nilai modern yang lintas batas. Referensi budaya seseorang tidak lagi pada kultur asalnya, tapi berkiblat pada kultur yang tercipta dari komoditi estetis yang ditampilkan di dalam televisi (Abdullah, 2007; hal 55-59). Dalam konteks masyarakat Muslim, dapat dikatakan bahwa kita terlempar dari fithrah yang suci ke suatu kubangan di ‘jagad rancu’, di mana semua norma menjadi bias dan semua hal serba relatif. Kita menjadi globalist-relativists.
Tren global ini kemudian menimbulkan apa yang disebut Baudrillard sebagai budaya konsumsi. Baudrillard mengatakan bahwa zaman ini telah menjadi era di mana orang membeli barang bukan karena nilai kemanfaatannya, namun karena gaya hidup, demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh iklan dan mode lewat televisi, tayangan sinetron, acara infotainment, ajang kompetisi bintang, gaya hidup selebriti, dan sebagainya. Yang ditawarkan saat ini bukanlah nilai guna suatu barang, tapi citra dan gaya bagi pemakainya (Baudrillard, 2006). Lebih jauh, ia menambahkan:
“Kita menjadi tak pernah terpuaskan. Kita lalu menjadi pemboros agung, mengonsumsi tanpa henti, rakus dan serakah. Konsumsi yang kita lakukan justru menghasilkan ketidakpuasan. Kita menjadi teralienasi karena prilaku konsumsi kita. Pada gilirannya ini menghasilkan kesadaran palsu. Seakan-akan terpuaskan padahal kekurangan, seakan-akan makmur padahal miskin”. (Baudrillard, 2006; 33)
‘Kehausan’ terhadap konsumsi berbasis gaya hidup tersebut, membuat orang berusaha memenuhi ‘kebutuhan’-nya dengan berbagai cara. Karena yang diperlukan adalah simbol, bukan utulity itu sendiri, maka sebagian kalangan menengah dan menengah ke bawah pun melakukan konsumsi simbolis, yakni mengkonsumsi tidak langsung pada barangnya, namun pada barang lain yang disimbolkan pada barang dengan kelas tertentu (Gerke dalam Damsar, 2002) Inilah kemudian yang menimbulkan pembajakan dan pengimitasian. Saya lebih suka menyebut situasi semacam ini sebagai hantaman ‘era konsumsi global’.
Era konsumsi merupakan konsepsi yang peneliti turunkan dari terminologi masyarakat konsumsi (la société de consommation) yang diperkenalkan oleh Jean Baudrillard, yang merujuk kepada suatu tatanan masyarakat yang hidup di era kelimpah-ruahan. Kelimpahan tersebut meliputi barang, jasa, bahkan budaya, yang mengkondisikan setiap manusia untuk terus-menerus mengkonsumsi sekalipun tidak membutuhkan (Ritzer, Pengantar dalam Baudrillard, 2004: xxxvii).
Era konsumsi ini sepadan dengan apa yang disebut Baudrillard dengan tahap perkembangan masyarakat pada fase fraktal (viral). Dalam fase ini, tidak ada yang disebut titik referensi, nilai-nilai memancar ke segala arah, menulari dan mengontaminasi setiap sudut kehidupan dengan sangat cepat, kemudian menghilang dan akhirnya dilupakan (Piliang, 2004: 165).
Apropriasi dan Simulakra
Appropriation dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata approval (penerimaan) dan appropriateness (kepantasan). Tindakan apropriasi, oleh karena itu, secara semantik dapat diterjemahkan sebagai upaya memantaskan diri terhadap suatu konteks (kondisi, ruang, waktu, objek atau lainnya) agar mendapatkan penerimaan yang layak. Nilai-nilai global yang dianggap sebagai referensi yang megandung ‘kebenaran’, membuat manusia melakukan upaya memantas-mantaskan diri terhadapnya. Namun upaya pemantasan terebut tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Di titik keterbatasan diri dalam melakukan pemantasan itulah kita menemui konsep Baudrilard tentang simulakra.
Simulakra kurang lebih diartikan sebagai konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas, tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial (Baudrillard, dalam Ritzer, 2008). Kamus Oxford menerjemahkan kata simulacrum (bentuk tunggal dari simulacra) sebagai “a thing resembling or made to resemble something” (1995;1102). Secara lebih spesifik, Baudrillard memberikan penjelasan sebagai berikut:
“So it is with simulation, insofar as it is opposed to representation. Representation starts from the principle that the sign and the real are equivalent (even if this equivalence is Utopian, it is a fundamental ax~om). Conversely, simulation starts from the Utopia of this principle of equivalence, from the radical negation of the sign as value, from the sign as reversion and death sentence of every reference. Whereas representation tries to absorb simulation by interpreting it as false representation, simulation envelops the whole edifice of representation as itself a simulacrum.” (Baudrillard, 1988: 169)
Jadi, manipulasi kenyataan yang menenggelamkan representasi ke dalam simulasi yang mereduksi ekuivalensi antara citra dan realitas (kendati sifat ekuivalen ini pun dianggap semu), itulah yang disebut simulakra. Inilah zaman di mana segala sesuatu diimitasikan, ditiru dan dipalsukan. Bahkan Cina sebagai sebuah negara raksasa telah “mencari makan” lewat geger budaya global ini dengan memproduksi dan memperdagangkan benda-benda imitasi. ’Baudrillard memandang zaman globalisasi ini telah menjadi era simulasi, di mana hiperrealitas menjadi bagian dari fase citraan.
Fase citraan tersebut, bisa diurutkan sebagai berikut: (1) citraan sebagai refleksi dasar realitas, (2) citraan yang menyelewengkan dasar realitas (3) citraan menutupi ketiadaan dasar realitas, dan (4) sampai akhirnya ia melahirkan dissinkronisasi terhadap realitas apapun, hingga yang ada adalah simulakrum itu sendiri, an sich. Di titik ini, mode menjadi kiblat dan agama. Pemaksaan gaya hidup menjadi sebuah keharusan untuk eksis. Di titik ini berlakulah prinsip; “biar miskin asal sombong.”
Merumuskan kembali budaya Indonesia
Dalam kompilasi tulisan Lifestyle Ecstasy (2004), Sapardi Djoko Damono bertanya dengan serentetan pertanyaan yang agak sulit dijawab: apakah kebudayaan Indonesia itu? Sudah adakah kebudayaan Indonesia itu? Apakah ia merupakan kumpulan puncak-puncak kebudayaan yang ada di Indonesia atau sesuatu yang sama sekali baru yang diciptakan tanpa mempedulikan masa lampau dan yang sudah ada sebelumnya? Apakah ia khas atau sama saja dengan kebudayaan bangsa lain?
Dalam tulisan yang sama ia kemudian mulai membicarakan soal ancaman “kebudayaan asing”, namun apalah arti kebudayaan asing, jika kita telah mengalami kerancuan tentang mana yang asing dan mana yang tidak? Di tengah kegegeran budaya ini, kita mesti melakukan dua hal. Pertama, meluruskan kembali pemahaman soal budaya dan melacak pada level mana perbaikan akan diadakan. Kedua, mengenali racun budaya utama, sembari menanamkan sistem imun terhadapnya. Ketiga, mengembangkan sikap mental yang positif terkait dengan interaksi budaya.
Koentjaraningrat (1993; 5) melihat budaya setidaknya terdiri dari tiga wujud:
1. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lainnya
2. sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
3. sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Pandangan sebagian orang yang mereduksi budaya hanya sampai tataran ketiga saja (yang sebenarnya hanya korteks, kulit luar), bahkan menganggap kebudayaan hanya setakat kesenian dan koleksi benda-benda, adalah pandangan sesat yang membuat kita tak kunjung bisa merefleksikan keagungan nilai budaya. Begitu pula jika kebudayaan hanya disambungkan sanad-nya pada kompleksitas pola kelakuan (adat), ia juga tak akan menemukan kesejatiannya. Maka kebudayaan haruslah berakar dari jiwa. Kebudayaan bersumber dari ide dan gagasan. kini, saat bangsa Indonesia mengalami kegamangan jiwa, kerancuan identitas, maka kegamangan dan kerancuan budaya jelas merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan.
Budaya kita, pada ketiga levelnya, telah menjadi sekadar budaya massa. Adapun aneka sendratari, kerajinan, dan rupa-rupa kesenian daerah, hanyalah basa-basi dan gerak-laku yang kehilangan makna. Damono dalam Ibrahim (ed. 2004; 5) memberikan pengertian budaya massa kurang lebih sebagai ‘budaya rendah’. Mass culture beranjak dari kata Jerman, masse dan kultur, yang merupakan lawan dari high culture. Mass atau masse menunjuk kepada masyarakat Eropa mayoritas (pada fase tersebut), yang berasal dari golongan menengah bawah, buruh dan kaum miskin yang tidak terpelajar dan non-aristokratik. Massa juga mengacu pada pengertian kelompok manusia yang tidak bisa dipilah, mirip kerumunan. Tidak ada individu dengan segala atribut dan keunikannya. Kebudayaan massa diciptakan dan hanya compatible dengan masyarakat serupa itu.
Tapi saat ini, dengan segala model lipatan dunia yang kita telah bicarakan sebelumnya, budaya massa ini menggurita, tidak hanya pada kalangan tertentu, tapi pada ‘kita’ semua. Tidak ada solusi yang lebih tepat kecuali mengembangkan sikap mental yang tepat dalam menghadapi ini semua. Mungkin solusi yang ditawarkan, tidak dapat disebut ‘solusi langsung’ karena memang tidak menyinggung hal-hal teknis. Tapi saya ragu, adakah langkah-langkah linier yang bisa memecahkan masalah yang bermunculan secara lateral bahkan viral/fraktal. Rasa-rasanya naif jika kita merumuskannya dalam program kerja atau time-schedule yang rigid, karena ini adalah masalah kejiwaan yang amat abstrak.
Pada saat yang sama, kita juga mesti arif bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang. Unit-unit budaya yang berbentur, bergesek, atau berbaur dengan budaya lain akan menghasilkan sebuah paduan baru yang memperkaya khasanah. Tidak mesti anti dengan budaya luar, lantas bersikap parokial. Tetapi pola adapting dan adopting selalu mesti dibarengi dengan prasyarat yang ketat berbasis kebenaran hakiki yang diyakini.
Rekayasa Budaya Elit
Di bagian akhir inilah saya ingin menyajikan apa yang disebut sebagai ‘solusi’ tadi. Rasanya tawaran-tawaran Kuntowijoyo menjadi sangat rasional untuk diperhitungkan. Kuntowijoyo terlebih dahulu mendedahkan perbedaan karakter budaya massa dan antonimnya, budaya elit. Budaya massa, menurut Kunto, adalah anak kandung massifikasi. Budaya massa adalah hasil perselingkuhan dari kebudayaan dengan industrialisasi dan komersialisasi, dalam hubungannya yang negatif (sebab ada kalanya industrialisasi dan komersialisasi berefek baik bagi perkembangan budaya).
Budaya massa berciri pada tiga hal (Kuntowijoyo dalam Ibrahim, 2004: 19) :
1. Objektivikasi; di mana pemilik budaya hanya akan menjadi objek; penderita yang tidak mempunyai peran apa-apa dalam pembentukan simbol budaya. Adakah para pemudi tanggung yang bercelana hipster turut mengkonstruksi mode? Tidak pernah! Mereka menjiplak habis-habisan idolanya dari video dan televisi tanpa pernah punya ruang untuk bertukar ide dan informasi, bahkan tanpa tahu alasan kenapa ia harus berdandan demikian rupa? Pemilik budaya massa hanya menerima produk budaya sebagai barang jadi dan tidak boleh bereran dalam bentuk apa pun.
2. Alienasi; pemilik budaya massa akan terasing dari dan dalam kenyataan hidup. Selanjutnya ia juga akan kehilangan dirinya sendiri dan larut dalam kenyataan yang ditawarkan produk budaya.
3. Pembodohan; yang terjadi karena waktu dan effort yang terbuang tanpa ada pengalaman baru yang dipetik dari praktik budaya sebagai bekal kehidupan selanjutnya.
Sementara budaya elit merupakan budaya tinggi. Ia juga berciri pada tiga hal yang berlawanan dengan ciri budaya massa:
1. Pemilik tetap menjadi pelaku (subjek budaya). Pemilik budaya tetap menjadi pribadi yang utuh, ttdak larut dan tenggelam dalam budaya. Ia tetap menjadi dirinya sendiri dan amat merdeka untuk menafsirkan apa yang dialaminya;
2. Oleh karenanya, pemilik budaya elit tidak mengalami alienasi. Ini disebabkan budaya elit menampilkan realitas tanpa polesan.
3. Konsekuensi logisnya, pelaku mengalami pencerdasan. Ia akan melalui berbagai pengalaman budaya dan belajar secara mandiri untuk menafsirkannya dalam kehidupan, sehingga mendapatkan kebijaksanaan. ia kemudian menjadi lebih pandai dan bijak dari sebelumnya.
Tentu selain mengadopsi budaya elit, ada daya dukung lain yang mesti diusahakan untuk mempercepat laju perubahan keadaan. Kuntowijoyo menawarkan dua cara mengatasi massifikasi, yang menurut hemat saya akan cukup sukses pula mengatasi semua pola fraktal dalam interaksi budaya di sebuah dunia yang tengah mengalami lipatan yang tidak karuan. Dua hal ini terkait dengan perilaku simbolik.
Pertama adalah privatisasi. Segala bentuk kegiatan yang menekankan pada kepemilikan pribadi yang khas ataupun keunikan yang tidak dimiliki orang lain, patut dikembangkan. Tapi mesti hati-hati, karena industri juga semakin cerdik. hal-hal yang sebelumnya sangat privat, juga dikomodifikasi menjadi produk massa. Ambil contoh bagaimana industri mengkapitalisasi deviant sub-culture semacam anak-anak Punk.
Kedua, spiritualitas, yakni adopsi budaya spiritual ke dalam kehidupan individu atau kelompok. Kata Kunto, “Dengan menyesal, atribut-atribut yang melambangkan kealiman terpaksa dimasukkan di sini”. Di kota-kota besar, hal ini mulai menemukan relevansinya. Segala macam kegiatan keagamaan (ke-Islam-an, khususnya) -bahkan yang aneh sekalipun- mulai diminati banyak orang. Yah, meskipun sebagian besarnya adalah keberagamaan yang artifisial, superfisial dan tidak terlalu terinternalisasi, tak apa lah. Solusi selanjutnya bisa diakali sambil berjalan, seiring bertambahnya waktu dan pengalaman.
Lantas bagaimana soal pertanyaan Sapardi di atas yang belum sempat dijawab? Harap dimaklumi bahwa makalah ringkas ini hadir hanya sebagai avant-propose, pra wacana. Diskusi-diskusi bagi dan atasnya lah yang akan menjawab itu semua. Wallahua’lam.
* Sebuah Tinjauan Sosio-filosofis Terhadap Masalah Budaya Indonesia. Disampaikan pada diskusi mingguan ISFI, Senin 17 April 2012, di IIUM
** Penulis, Andree, adalah mahasiswa program Doktoral jurusan Sosiologi dan Antropologi, IIUM
Daftar Bacaan :
Abdullah, Irwan. (2007). Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Baudrillard, Jean. (2004). Masyarakat Konsumsi. Terjemahan Wahyunto. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
_______________. (1988). “Simulacra and Simulation”, in Selected Writings. ed. Mark Poster. Stanford: Stanford University Press.
Cano, Alonso Guiomar, et.all. (2005). Kebudayaan, Perdagangan dan Globalisasi. Terjemahan PeMad. Yogyakarta: Kanisius.
Damono, Sapardi Djoko. “Kebudayaan Massa dalam Kebudayaan Indonesia: Sebuah Catatan Kecil”, dalam Ibrahim, Idi Subandy (ed.). 2004. Lifestyle ecstasy: Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat Komoditas Indonesia. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
Damsar. (2002). Sosiologi Ekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Koentjaraningrat. 1993. buga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
Kuntowijoyo. “Budaya Elit dan Budaya Massa”, dalam Ibrahim, Idi Subandy (ed.). 2004. Lifestyle ecstasy: Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat Komoditas Indonesia. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
Nasikun. 2007. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Oxford Dictionary Team. (1995). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press.
Piliang, Yasraf Amir. (2004). Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra.